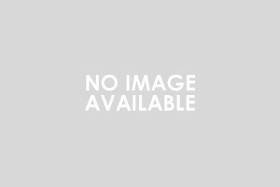Kehidupan di Bahodopi: Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan
Beberapa hari berada di Morowali membuat paradoks hilirisasi terasa nyata. Di Bahodopi, jantung kawasan industri nikel, roda ekonomi berputar cepat. Hotel penuh, rumah makan ramai, toko kelontong buka hingga larut malam. Namun di balik hiruk pikuk itu, keluhan masyarakat dan pekerja sama: infrastruktur dasar tertinggal.
Jalan utama, jalur Trans-Sulawesi, sempit dan rusak, melambungkan biaya logistik serta harga bahan pokok. Gas melon bisa mencapai Rp80 ribu. Warga juga mengaku listrik sering padam meski berdiri PLTU besar untuk menopang smelter, yang justru memicu polusi hingga atap seng rumah hanya bertahan dua bulan. Sekolah negeri kewalahan, dengan hanya satu SMA Negeri di Bahodopi, membuat banyak anak harus sekolah di luar wilayah. Harga hunian melonjak, memaksa pekerja tinggal jauh dan menempuh perjalanan panjang, atau bertahan di pemukiman kumuh dekat kawasan demi harga terjangkau.
Nelayan kehilangan mata pencaharian akibat pencemaran laut, antara nekat melaut jauh berhari-hari dengan perahu kecil atau beralih memulung sampah plastik seharga Rp3 ribu per kilogram. Kontras juga terlihat antara Bahodopi dan Bungku, ibu kota kabupaten. Bahodopi sibuk, Bungku lengang, menegaskan manfaat pertumbuhan tidak merata.
Data Memperjelas Kesenjangan
Data memperjelas kesenjangan ini. Pada 2024, PDRB per kapita Morowali mencapai Rp1 miliar, tertinggi di Indonesia, dengan rata-rata nasional hanya Rp78,6 juta. Namun pengeluaran per kapita Morowali hanya sekitar Rp2 juta per bulan, tidak jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional Rp1,5 juta, atau setara hanya 2,4% dari output daerah.
Padahal, pada 2014, pengeluaran per kapita masih 21,9% dari PDRB per kapita, mirip rata-rata nasional 22,3%. Tahun 2019, angkanya di Morowali jatuh ke 4,2%, sementara nasional tetap 23,7%. Jurang semakin melebar pada 2024: nasional 22,9%, Morowali tinggal 2,4%. Dalam satu dekade, Morowali bergeser dari “normal” menjadi contoh ekstrem decoupling antara output dan kesejahteraan.
Indikator lain menambah bukti ketimpangan dan penghisapan ke luar. Tahun 2023, PDRB Morowali Rp158 triliun, tetapi realisasi pendapatan daerah hanya Rp1,98 triliun, dengan PAD Rp596 miliar atau hanya 29,9%. Output melonjak, kapasitas fiskal tetap kecil. Rente tak banyak tinggal di daerah, sedikit banyak menjelaskan masih buruknya kualitas infrastruktur dasar.
Tren Pertumbuhan Ekonomi dan Sinyal Peringatan
Tren pertumbuhan ekonomi juga menguatkan sinyal peringatan. Setelah melesat 28,7% (2021), pertumbuhan Morowali turun ke 25,3% (2022), lalu 20,3% (2023), hingga 16,26% pada 2024, disinyalir seiring jatuhnya harga nikel global. Fondasi pertumbuhan yang bergantung pada boom komoditas terbukti rapuh.
Fenomena Enclave dan Ancaman yang Semakin Nyata
Investasi memang besar-besaran. PT IMIP mengklaim akumulasi investasi sejak 2015 hingga 2024 telah mencapai Rp562 triliun. Puluhan smelter berdiri cepat, menjadikan Morowali simpul penting rantai pasok global baterai kendaraan listrik. Namun investasi spektakuler ini ternyata tak otomatis memperluas kapasitas fiskal daerah atau menaikkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
Kawasan Industri PT IMIP menjadi episentrum paradoks ini. IMIP dirujuk pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan disebut Obyek Vital Nasional (OVN). Status ini memberi akses insentif fiskal, prioritas infrastruktur, kemudahan izin, dan perlindungan keamanan. Dengan kata lain, IMIP adalah enclave yang “dilindungi negara”: risiko bisnis minim, keuntungan terjaga, sementara integrasi dengan ekonomi lokal terbatas.
Fenomena ini sejalan dengan peringatan tradisi teori ketergantungan Amerika Latin. Cardoso dan Faletto (1969 [2021], hlm. 72) mencatat bahwa proses pertumbuhan berskala besar di Amerika Latin “pada dasarnya merupakan hasil langsung dari ekonomi enclave… dengan aliansi politik lokal… yang bernegosiasi dengan sektor eksternal… dan diterima oleh sektor-sektor oligarki yang dominan”. Dengan kata lain, dominasi kapital asing dan aliansinya dengan oligarki lokal membuat pembangunan seringkali terjebak dalam logika enclave. Morowali memperlihatkan hal tersebut: output melonjak, tetapi manfaat tidak optimal menetes ke masyarakat.
Solusi: Dari Smelter ke Integrasi dan Diversifikasi
Apa jalan keluarnya? Tradisi ketergantungan menekankan perlunya negara menegosiasikan ulang relasi dengan kapital asing dan oligarki agar pertumbuhan tak terjebak dalam enclave. Tradisi negara pembangunan menuntut birokrasi yang otonom dari kepentingan oligarki sekaligus tertanam dalam jaringan sosial-ekonomi agar rente diarahkan ke pembangunan inklusif.
Secara teknis, hilirisasi harus dipahami bukan sebagai tujuan akhir, melainkan langkah awal transformasi struktural.
- Pertama, pemerintah perlu memperluas joint ventures antara investor asing dan perusahaan lokal agar transfer teknologi benar-benar terjadi.
- Kedua, redistribusi rente ke pemerintah daerah harus diperkuat sehingga PAD meningkat dan bisa membiayai sekolah, rumah sakit, listrik desa, serta infrastruktur publik lain.
- Ketiga, backward linkages harus dibuka lebih luas guna memberdayakan UMKM lokal, dari suplai logistik hingga bahan penolong.
- Keempat, forward linkages perlu dipacu agar hilirisasi tidak berhenti pada produk antara, tetapi berlanjut hingga baterai kendaraan listrik itu sendiri.
- Kelima, rente nikel harus diarahkan mendukung diversifikasi industri, termasuk sektor padat karya seperti elektronik, tekstil, dan peralatan transportasi. Dengan begitu manfaat industrialisasi hijau bukan hanya sukses di atas kertas, tetapi juga dirasakan di kantong dan dapur masyarakat.
Penutup
Morowali adalah peringatan sekaligus peluang. Bahodopi sibuk, Bungku sederhana. PDRB melonjak, konsumsi rumah tangga tertinggal. Jika pemerintah puas dengan capaian smelter, hilirisasi komoditas lain berisiko mengulang pola sama: pertumbuhan tinggi tetapi enclave. Namun bila pemerintah berani menuntut lebih, baik dari investor maupun dirinya sendiri, hilirisasi bisa jadi batu loncatan menuju industrialisasi hijau yang terintegrasi dan berkeadilan.
RPJMN 2025–2029 telah menempatkan hilirisasi sebagai tulang punggung industrialisasi Indonesia. Morowali adalah ujian pertama: apakah hilirisasi hanya akan tercatat sebagai angka pertumbuhan, atau sungguh menjadi strategi pembangunan? Dengan status PSN dan OVN, pemerintah pusat punya ruang intervensi besar. Pertanyaannya, apakah status istimewa itu terus dipakai melindungi enclave, atau dijadikan instrumen untuk memaksa integrasi, transfer teknologi, dan redistribusi kesejahteraan?